MEUGAPAIH
GAPAIH, adalah lemak yang di bawah kulit. Di gampong-gampong, orang-orang yang banyak gapaihnya dianggap sebagai orang yang sehat.
Pasal, kalau kita ditanyai orang kita, siapakah orang-orang yang meugapaih itu? Jawabannya pasti hanya “orang kaya”. Padahal belum tentu. Di gampong saya, seorang anak miskin juga terlihat meugapaih. Hanya saja beda antara dia dengan anak orang kaya, kalau dia selalu makan nasi berulangkali, sedang anak orang kaya selalu makanan siap saji atau makanan yang disediakan di pusat-pusat jajanan. Paling tidak, berbungkus indomie yang akan dimakan tiap hari.
Atas dasar itulah, bila ada orang yang berlainan perilaku dengan keadaan sesungguhnya, selalu disebut, “bak kareng pih ka meugapaih”. Orang Aceh sedang mengingatkan, ungkapan, di mana langit dijunjung, di sana bumi dipijak. Tak mungkin seseorang ingin melakukan yang lebih dari kemampuannya.
Ungkapan “bak kareng pih ka meugapaih” itu ternyata menjadi perbincangan di balee gampong. Memang terdengar usang, tapi saya rasa masih mengena. Disebut usang, karena ungkapan-ungkapan ini sepertinya hanya cocok untuk masa lalu. Namun setelah ditimbang-timbang, rasa-rasanya, ungkapan itu jauh lebih cocok untuk masa depan –masa yang mungkin akan kita nantikan dengan berbagai kejutan dan fenomena yang belum terlihat.
Kejutan dan fenomena ini bisa saja sudah mulai bisa dirunut lewat berbagai gejala. Tapi itu persoalan lain. Masalahnya, bagaimana masa lalu dengan sekarang dan masa yang akan datang menarik benang merahnya walau dalam wajah yang sudah kusut. Dan, itu memang akan sulit dilepas.
Ada empat ungkapan berbeda. Tapi saya yakin, ketiganya bermaksud sama dalam kehidupan keseharian masyarakat Aceh. Dari ketiga ungkapan itu, juga melahirkan tanda tanya besar bagi saya sendiri: mengapa orang Aceh mengeluarkan ungkapan-ungkapan selalu berterminologikan hewan atau binatang. Bahwa, ada perbedaan yang sangat tajam, saat seseorang menyebut kepada orang lain (bisa jadi keluarga, teman, atau kawom) dengan jenis-jenis binatang. Ungkapan “gata lagee leumo” akan berbeda dengan ungkapan “gata lagee peulandok” atau “gata lagee rimueng”. Saya yakin, kita masih beranggapan ketiga contoh tersebut (leumo, peulandok, rimueng), semuanya adalah jenis-jenis binatang.
Masalahnya, walau ketiga-tiganya jenis binatang, sepertinya tidak bisa kita menyamaratakan sebutan terhadap orang-orang. Seorang teman, yang kita samakan dengan peulandok, akan bersama konsekuensinya yang kita terima bila kita samakan dengan rimueng atau leumo –apalagi kalau kameng, uleue, guda, dan binatang-binatang yang haram disentuh. Padahal sama-sama binatang.
Seorang teman bisa saja akan tersenyum senang bila kita sebut “gata lagee peulandok”. Tapi senyuman itu bisa saja tidak hadir (atau bahkan berubah menjadi murka) saat kita menyebut, “gata lagee leumo” atau “rimueng” atau “kameng”, dan sebagainya. Padahal, sekali lagi, semua itu adalah binatang.
Mungkinkah ini sebagai bentuk pelembutan sebuah sebutan? Lihatlah keempat ungkapan di bawah ini.
Pertama, le jilho ngoen jirod. Ungkapan ini, saya kira hanya diperuntukkan bagi dua jenis binatang gembala: keubeue dan leumo. Binatang yang jipeu umpeun, ia tak akan memakan lagi rumput di padang. Katanya, “untuk apa saya makan kalau nanti pulang ke kandang juga akan tersedia makanan”.
Kedua, ka meuhai taloe ngoen keubeue. Bayangkan juga, “ka meuhai minyeuk ngoen moto”. Sudah pasti, orang yang ingin memiliki keubeue atau moto, tak ingin biaya untuk bisa naik ke atasnya jauh lebih besar dari harganya.
Ketiga, ka kreuh bhan keue ngoen bhan likoed. Saya sarankan, sesekali, kita yang memiliki sepeda atau sepeda motor, untuk lebih mengempeskan ban belakang ketimbang ban depan. Rasakanlah (mungkin) hal-hal yang belum kita nikmati selama ini. Selain itu, lihatlah dua orang yang berbeda: (a) orang yang bersepeda motor yang ban motor depannya bocor. Lalu, bandingkan dengan: (b) orang yang bersepeda motor yang ban motornya belakangnya bocor. Dari dua orang itu, lihat cara mengemudinya, cara duduknya, sampai pada kecepatannya.
Keempat, bak-bak kareng ka jiduek gapah. Ingatlah, “Ngui meunurot tuboh, pajoh meunurot atra”. Bayangkan, seseorang yang kerempeng memakai baju besar. Seorang bertubuh mungil memakan tiga tabak khanduri. Di samping ada keanehan, juga akan terlihat ketidaknormalan. Itu pasti.
Gapah itu dominan pada leumo seu’iet. Tapi sedikit pada kareng. Ini bukan berarti kareng tak diinginkan orang. Kareng yang teulado, banyak orang yang tidak bisa melupakannya. Adakalanya, orang-orang yang kepingin makan ikan kareng jauh lebih dahsyat ketimbang keinginan untuk memakan sepotong sie keubeue atau sie leumo.
Maka wajar kalau sesekali kareng pun harus merasakan dirinya meugapaih.[]
Sulaiman Tripa
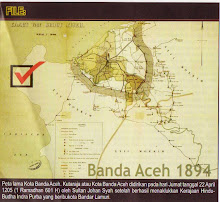

0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda