qanun di Aceh
PEMBENTUKAN QANUN DI ACEH
(Sulaiman Tripa)
Ada dua fenomena menarik perihal keberadaan qanun di Aceh, yakni: Pertama, qanun kalah cepat dengan pertumbuhan kota (Serambi, 05/04/09). Disebutkan bahwa sebuah perangkat hukum atau qanun yang dibutuhkan dalam menyahuti pesatnya pertumbuhan Kota Banda Aceh, ternyata belum mampu dipenuhi. Berita ini terkait dengan kondisi dimana pembangunan pertokoan atau bangunan liar (tanpa IMB) terus menjamur dan tanpa terbendung. Pembangunan pertokoan sebagai cermin geliat perekonomian yang terus tumbuh. Namun IMB sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) belum bisa tergarap secara optimal. Intinya, sebagian pihak menyebutkan bahwa revisi Qanun Tata Ruang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan sektor pendapatan. Revisi qanun berkaitan dengan denda yang sangat kecil bila dibandingkan dengan nilai asset.
Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya menghasilkan 18 qanun dalam setahun (Serambi, 05/04/09). Dari 18 qanun, hanya satu qanun dari inisiatif dewan. Sedangkan qanun lainnya semua hasil inisiatif dan prakarsa eksekutif. Ke-18 qanun tersebut, antara lain Qanun Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Pidie Jaya, Qanun APBK 2008, Qanun Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong, Qanun Pengelolaan dan Aset Daerah, Qanun Pajak Galian Golongan C, Qanun Pajak Sarang Walet, Qanun Retribusi Pelayanan Pasar, Qanun Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Qanun Perubahan APBK 2008, Qanun Retribusi Gangguan (HO), Qanun Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan, Qanun Retribusi Surat Izin Tempat Usaha, Qanun Setdakab dan Sekwan, Qanun Dinas dan LTD, Qanun Kecamatan, Qanun Retribusi IMB, dan Qanun APBK 2009.
Ada persamaan dari dua berita tersebut, yakni bagaimana qanun dipandang sebagai media untuk meningkatkan kesejahteraan dalam wujud materil berupa pendapatan asli daerah. Di sini, saluran meningkatkan kesejahteraan seolah-olah hanya dimungkinkan melalui pendapatan asli daerah semata. Padahal kalau kita maknai secara kritis, bahwa sebenarnya konteks kesejahteraan tak hanya melalui pemasukan pendapatan saja. Sebaliknya, konteks kesejahteraan bisa dilihat dengan tidak banyak dana yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki kehidupan sosial.
Ada contoh menarik dalam perkembangan pasca pelaksanaan otonomi di Indonesia –termasuk di Aceh, yakni ada kecenderungan kebijakan di daerah untuk membuka peluang selebar-lebarnya dalam rangka mengeksploitasi potensi alam untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya. Banyak daerah yang menjadikan galian golongan C sebagai pendapatan potensial bagi daerahnya. Namun pada saat yang sama, sebenarnya ada kerusakan yang harus ditanggung, kadangkala untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan social membutuhkan dana yang lebih besar dari pendapatan yang dikumpulkan. Kerusakan aliran sungai, pada kenyataannya membutuhkan dana pembangunan untuk merehabilitasinya. Bila diukur-ukur, maka biasanya dana untuk merehab jauh lebih besar ketimbang dana yang didapatkan dari pendapatan PAD.
Dalam kasus banjir, galian C juga turut memberi pengaruh. Kita semua tahu bahwa kerugian akibat banjir tidak pernah dihitung secara konkret. Padahal bila semua kerugian akibat banjir dihitung dengan cermat, belum tentu kerugian yang dialami masyarakat lebih rendah ketimbang pendapatan dari sektor tersebut.
Dalam hal ini, sudah seyogianya pertimbangan-pertimbangan sosial seperti di atas turut diperhatikan dalam merumuskan sebuah qanun. Sebuah produk perundang-undangan tidak hanya dilihat akan menghasilkan apa saja, namun penting juga untuk mempertanyakan konsekuensi apa yang akan dirasakan masyarakat karena hadirnya qanun tersebut.
Sebuah qanun seperti ini memberi kita pilihan. Masalahnya adalah kita akan memilih yang mana. Acapkali kita akan memilih peluang untuk menghasilkan sejumlah nilai pendapatan yang konkret, dan mengabaikan ancaman terhadap kerugian sosial yang bakal dialami. Dengan nilai pendapatan tersebut, kerapkali membuat kita subjektif dalam melihat permasalahan. Misalnya pendapatan dari sektor hutan sekian rupiah, seyogianya harus memperhitungkan sebesar apa kerugian sosial yang akan dialami masyarakat bila berulang-ulang merasakan banjir.
Ketepatan dalam melihat pilihan tersebut, akan sangat menentukan kita akan memihak kemana. Ada sebuah gurauan masa lalu yang pernah diungkapkan oleh seorang Sosiolog, bahwa ada kecenderungan daerah untuk mengejar menyelesaikan qanun yang Rp ketimbang qanun yang PR. Qanun-qanun yang Rp (rupiah) biasanya berkaitan dengan hal-hal pendapatan. Sementara qanun PR (pekerjaan rumah), adalah qanun-qanun yang berhubungan langsung dengan konsep mensejahterakan (dalam arti luas) masyarakat.
Untuk jangka pendek, qanun-qanun Rp sebenarnya juga dikampanyekan untuk mensejahterakan rakyat (dalam arti sempit). Namun kesejahteraan itu dihantui oleh pengrusakan yang jauh lebih hebat. Di sinilah dalam konteks potensi alam, perlu dilakukan penolakan sebuah rumus “modal kecil untuk untung yang besar”.
Berkaitan dengan keberadaan izin mendirikan bangunan (IMB), pertimbangan kesejahteraan ini juga harus diperhatikan. Seyogianya IMB tak hanya berkaitan dengan pendapatan. Masalah tata ruang terkait dengan sebuah sistem pengelolaan ruang yang luas. Jangan sampai karena ada peluang meraih pendapatan dari sektor ini (ekonomi), sementara mengabaikan faktor lingkungan, sosial, budaya, bahkan nilai religi menjadi dinomorduakan. Karena pengabaikan faktor-faktor tersebut pada akhirnya akan membawa kerugian yang berlipat-lipat ketimbang pendapatan yang diperoleh.
Seperti inilah yang saya maksudkan bahwa penting memahami berbagai pertimbangan dalam menentukan pilihan dalam merumuskan qanun. Bila setiap qanun dalam proses pembentukannya selalu mempertimbangkan hal-hal begini, maka dapat dibayangkan betapa luar biasa ribuan qanun yang sudah dihasilkan di Aceh. Ribuan qanun ini dihitung, bila satu Kabupaten/Kota rata-rata sudah menghasilkan 40-50 qanun, maka di Aceh paling tidak sudah ada 1.000 qanun (pendapat ini pernah disampaikan Dr Mahdi Syahbandir, dosen FH Unsyiah di harian ini).
Proses ini memang berat. Karena dengan program legislasi yang telah disusun, rata-rata daerah masih harus menyelesaikan proyeksi qanun. Harus diselesaikan, berarti ada kaitan dengan, ‘keharusan’, ‘kemestian’, ‘wajib’, untuk mengisi aturan hukum karena kekosongan dan / atau karena tidak up to date peraturan yang sudah ada.
Sejumlah gejala yang juga beriringan dengan penyelesaikan qanun tersebut, adalah cepat usangnya qanun yang sudah ada atau dibuat. Banyak qanun yang kemudian direvisi atau diharapkan masuk dalam program legislasi untuk dilakukan revisi. Gejala ini, bila dibongkar dari dasar, tentu karena ada masalah di dalamnya. Masalah tersebut, antara lain karena tidak ada kematangan saat penyusunan, serta dangkalnya kajian yang menyangkut dengan pembentukan qanun.
Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa sebuah qanun diharuskan memenuhi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Ketiga aspek ini sebagai catatan paling dasar dalam menyusun sebuah qanun.
Di samping itu, bila kita merujuk Pasal 2, Pasal 11, dan Pasal 20 Qanun Nomor 3 Tahun 2007, maka ada beberapa hal yang juga wajib diikuti. Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, keterlaksanaan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan, dan keterlibatan publik. Konsepsi rancangan qanun, berisi antara lain latar belakang dan tujuan penyusunan, dasar hukum, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, jangkauan serta arah pengaturan, dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.
Batasan tersebut, secara implisit juga mengharuskan dalam membentuk qanun untuk melihat rakyat sebagai sasarannya. Konsep untuk kesejahteraan dalam arti luas yang menjadi harapan banyak orang, sebenarnya adalah konsep menuju kebahagian bagi masyarakat kita.[]
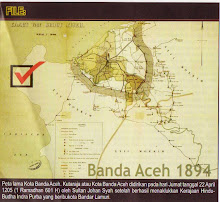

0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda