ROKOK
> > Sulaiman Tripa
(Harian Serambi Indonesia, Kamis, 4 Februari 2009)
Laporan Departemen Kesehatan, menempatkan Aceh paling jorok dalam hal merokok (Serambi, 3/2/09).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Aceh merupakan salah satu kawasan orang-orang yang banyak mengonsumsi rokok.
Bila saja kita baca kembali apa yang disebutkan pada setiap bungkus rokok, “merokok dapat menyebabkan kanker, impotensi, penyakit jantung, dan gangguan kehamilan,” berarti karena rokok (akan) menyebabkan perokok di Aceh mendapatkan penyakit-penyakit yang tersebut pada bungkus rokok. Artinya, bila seseorang di Aceh sakit, maka ia akan berobat di Aceh, bukan di luar Aceh. Konkretnya, Aceh butuh rumah sakit atau lembaga medis atau obat-obatan untuk menanggulangi kemungkinan tersebut.
Itulah tali-temali dari sebatang rokok. Sekilas apa yang diungkapkan di atas, memperlihatkan bahwa dari sebatang rokok sudah memperlihatkan kompleksitas permasalahan, yang semua itu kemudian menjadi problematika.
Bila permasalahan rokok dalam konteks itu, maka tidak bisa tidak, bahwa Pemerintah harus memikirkan bagaimana menanggulangi ekses dari aktivitas merokok. Pemerintah harus menyediakan jasa layanan medis untuk penyakit yang ditimbulkan dari sebatang rokok.
Masalahnya kemudiaan yang muncul adalah mengapa untuk Aceh tidak ada dana pembagian hasil dari penerapan Pasal 66A UU No. 39/2007 tentang Cukai? Bukankah salah satu filosofis dari UU Cukai adalah untuk menanggulangi ekses yang timbul dari rokok?
Dalam Pasal 66A UU Cukai disebutkan bahwa, cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagi-hasilkan kepada daerah karena barang kena cukai berupa hasil tembakau memiliki sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan dan diawasi serta memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari cukai –pengendalian dan pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Tahun ini, bagi hasil dari tembakau (sebanyak 2 persen) didapat oleh daerah: Sumatera Utara sebanyak Rp1,4 miliar, Jawa Barat Rp9,5 miliar, Jawa Tengah Rp52,2 miliar, Daerah Istimewa Yogyakarta Rp1,1 miliar, dan Jawa Timur Rp135,8 miliar.
Lima daerah yang mendapatkan dana bagi hasil tersebut adalah daerah penghasil rokok. Sementara daerah penghasil tembakau atau penghasil cengkeh, sama seperti Aceh, juga tidak mendapat bagian. Padahal dari sebatang rokok, selain membutuhkan pengonsumsi, juga membutuhkan andil daerah penghasil tembakau dan cengkeh. Namun ternyata UU hanya melihat produsen rokok semata, dalam hal ini kawasan industri rokok.
Sesampai di sini, sudah ada dua catatan kritis yang harus diberikan kepada UU Cukai, yakni: Pertama, fokus UU Cukai hanya pada daerah industri rokok, padahal produksi rokok secara nasional tergantung pada pasokan tembakau dan cengkeh. Kedua, besarnya cukai rokok yang masuk ke kas negara disebabkan oleh banyaknya para perokok, dan para perokok ini tidak selalu berasal dari daerah penghasil rokok. Artinya, bisa jadi bukan daerah penghasil rokok yang justru akan banyak mendapatkan ekses dari merokok.
Makanya menjadi patut menanyakan kembali bagaimana dengan daerah yang menerima ekses dari aktivitas merokok seperti Aceh? Hal ini penting, karena dana bagi hasil sebagaimana ditentukan UU Cukai adalah untuk memperbaiki ekses dari orang merokok.
Di samping itu, dalam UU Cukai sendiri masih terdapat dua pengaturan yang berseberangan. Di satu pihak, daerah penghasil rokok diharuskan ”mengkampanyekan” rokok agar pendapatan dari sektor cukai bisa meningkat. Namun pada pihak lain, rokok dimasukkan dalam kategori cukai karena berimplikasi luas kepada kesehatan, sehingga cukai rokok dinaikkan sampai 275 persen diharapkan akan mengurangi para perokok. Dalam Pasal 5 UU Cukai, seperti menjadi tawaran solusi pembatasan rokok, yakni tingginya tarif cukai yang mencapai 275 persen. Dalam penjelasan disebutkan bahwa pertimbangan tarif cukai demikian diakibatkan karena sifat atau karakteristik rokok yang berdampak negatif bagi kesehatan.
Bukankah kenyataan tersebut menampakkan bahwa UU sendiri berparas ganda? Disadari betul bahwa rokok ada efek negatif, namun pendapatan dari cukai terus digenjot. Tentu saja, perokok harus lebih banyak dari tahun ke tahun.
Sebagai informasi, bahwa pendapatan dari sektor cukai sangat menggiurkan dari tahun ke tahun. Target penerimaan cukai tahun 2009 adalah Rp49,49 triliun. Cukai rokok tahun 2008 senilai Rp44,4 triliun (dengan 227 miliar batang rokok) –RAPBN 2009 Rp47,49 triliun. Pada 2007 dengan target Rp42,03 triliun (224 miliar batang) saja –RAPBN 2008 Rp45,72 triliun, daerah penghasil mendapat Rp800 miliar. Bila melihat dana dari cukap rokok dari tahun ke tahun, mulai dari 2000 (Rp11,29 triliun), 2001 (Rp17,39 triliun), 2002 (Rp23,19 triliun), 2003 (Rp26,28 triliun), 2004 (Rp triliun 29,17), 2005 (Rp33,26 triliun), 2006 (Rp37,77 triliun), 2007 (Rp42,03 triliun), dan 2008 (Rp45,72 triliun).
Apa yang tergambar dari angka-angka di atas? Ternyata, rokok yang hisab sebatang demi sebatang itu telah menjadi sumber pemasukan besar bagi keuangan negara. Dengan jumlah angka hampir mencapai Rp50 triliun itu, rasanya menjadi berat bila sampai ada pembatasan terhadap aktivitas merokok.
Permasalahan tidak selesai sampai di sini. Membatasi rokok, oleh sebagian pihak juga dianggap sebagai ancaman mengerikan bagi sekitar 200 ribu pekerja di pabrik rokok. Rokok yang kita hisab tersebut, dengan demikian sudah menghidupi 200 ribu keluarga. Belum lagi untung yang diperoleh oleh para penjual rokok dari kios sampai mall mewah.
Atas berbagai gambaran, kemudian seperti sebuah kewajaran ketika Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2008 lalu mengumumkan bahwa Indonesia adalah negara terbesar ketiga pengguna rokok, dengan lebih dari 60 juta penduduk Indonesia tidak berdaya karena terjajah adiksi nikotin. Jumlah perokok memperkaya kontribusi terhadap pemasukan negara.
Tapi ada yang patut digelisahkan. Kematian akibat konsumsi rokok lebih dari 400 ribu orang per tahun. Konsumsi rokok di kalangan remaja meningkat 144 persen antara tahun 1995-2004. Lembaga Demografi UI menyebutkan rokok telah menggerogoti sumber keuangan rumah tangga miskin karena membelanjakan 12,4 persen pendapatnya untuk membeli rokok, dan mengorbankan gizi keluarga, kesehatan, dan pendidikan.
Katanya, rokok adalah musuh bagi semua negara beradab –bahkan sudah 160 negara meratifikasi Kerangka Konvensi Pengendali Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC). Indonesia turutserta dalam menyusun FCTC, namun hingga sekarang belum meratifikasinya.
Seorang teman saya yang merokok berat pernah berseloro. Katanya, ia menyadari bahwa merokok akan berefek penyakit bagi dirinya dalam waktu yang lama, namun ketiadaan rokok, justru akan mempercepat kena penyakit itu.
Jelaslah, bahwa ada sisi mengerikan, ada sisi kenikmatan. Pemasukan dari cukai dianggap membawa kesejahteraan, sementara implikasi kepada kesehatan (dengan mengeluarkan anggaran) tidak dianggap sebagai ancaman. Padahal menurut saya, kesejahteraan juga bisa dimaknai ketika negara tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk mengobati orang sakit.
Saya hanya ingin mengingatkan bahwa betapa sebatang rokok memperlihatkan kompleksitas. Sudah seyogianya ada perubahan paradigma. Negara –melalui aparaturnya tidak selalu harus melihat pemasukan sebagai satu-satunya jalan kesejahteraan. Sementara rokok tak harus dipandang sebagai simbol kedigdayaan, simbol keberhasilan, atau jalan pergaulan.
Mengubah paradigma ini sangat berat, karena di saat yang sama produsen rokok secara berjamaah membiayai proyek iklan raksasa yang luar biasa. Iklan rokok dikeluarkan besar-besaran untuk membiayai band-band yang digandrungi anak muda, membiayai olahraga, bahkan tega sekali banyak produsen rokok menjadikan perempuan (yang di bawah kakinya kita mendapatkan surga) dengan pakaian minim sebagai medianya. Bahkan produsen rokok juga menyediakan yayasan untuk membiayai anak-anak muda yang pandai.
Bukankah makin kompleks saja?
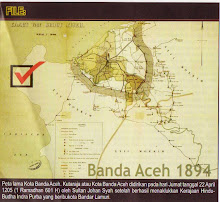

0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda