BUYA & MURUWA
Sulaiman Tripa
(Raja Post, 25 Maret 2006)
DULU, ada sebuah tamsil yang sering diungkapkan para orang tua: buya krueng teu dong-dong, buya tamong meuraseuki. Kini, tamsil itu sudah berubah, dan tak hanya diungkapkan oleh para orang tua, menjadi: buya krueng teu dong-dong, meuruwa tamong meuraseuki.
Awalnya, saya tak menangkap ada perbedaan antara kedua binatang itu. Dalam tulisan, saya juga harus mempelajari, makna buya dan meuruwa.
Untuk menemukan aktivitasnya, berkali-kali saya harus menunggu berbagai film di televisi tentang dunia hewan untuk mencari perbedaan itu. Saya harus menunggu Planet Animals, Flora dan Fauna, Wild Life, Wild Animal, dan masih banyak yang lain, di berbagai stasiun televisi.
Dari berbagai acara di televisi itulah, setelah memperhatikan secara detail, saya mendapatkan perbedaan, walau masih sekilas. Mulai dari bentuk fisik, sampai perilaku: buya dan meuruwa.
Dari segi fisik, tampak jelas ukuran buya jauh lebih besar. Bahkan disebutkan, ada buya yang beratnya mencapai setengah ton. Sedangkan meuruwa, tak ada yang lebih berat dari lima puluh kilogram.
Bagaimana pun buya jauh lebih sangar ketimbang meuruwa. Tingkah-polah Buya lebih agresif, lebih bengis, dan tak bersahabat. Bahasa Acehnya, juwah. Tak pernah kita mendengar ada meuruwa yang memangsa anak manusia, konon lagi yang sudah dewasa. Tapi buya sering memangsa manusia.
Di gampong saya, orang tua menggunakan jurus buya untuk menakuti anak-anaknya yang keganjingan mandi di sungai sampai puas, yang biasanya ditandai dengan bola mata yang sampai memerah. Mereka akan diingatkan agar tak terlalu banyak waktu dihabiskan di sungai.
Mungkin juga di banyak kawasan lain di Aceh, para orang tua akan mengatakan: jangan pergi ke krueng, nanti buya akan jipajoh keuh, ia akan memakannya bulat-bulat bila ukuran tubuh kecil.
Kabar terakhir di Lancang Paru, beberapa tahun lalu, ada seorang anak yang di kap kakinya oleh buya tamong di kuala.
Bila mendengar kabar itu, seluruh orang gampong akan keluar mencari buya. Orang gampong akan membunuhnya dan akan membelah perutnya untuk mengambil organ-organ manusia yang dimakan buya.
Ketika dulu uleue-uleue besar masih ada di gampong-gampong dan memangsa anak-anak, masyarakat gampong juga akan mencari dan membunuhnya untuk dibunuh dan dibelah perutnya. Bila ada orang yang dimangsa meninggal dunia, maka organ yang dimakan akan diambil dari dalam perut untuk di-fardhukifayah-kan secara layak dengan segera.
Saya hanya mau menceritakan bahwa buya memang lebih juwah ketimbang meuruwa. Bila melihat manusia, apalagi manusia akan menggangu sarangnya, buya akan menantang. Buya tak akan bersurut, barang selangkah pun. Berbeda dengan meuruwa yang lebih memilih angkat kaki seribu.
Terutama karena perilakunya yang tidak bersahabat, maka buya jauh lebih takuti ketimbang meuruwa. Yang sangat menarik, walau buya lebih ditakuti karena sering memangsa manusia, ternyata meuruwa yang paling dibenci.
Pernah suatu kali saya sempat berdiskusi kecil di sebuah bale gampong di Samalanga. Seorang tua yang berumur sekitar 60-an tahun, mengatakan, meuruwa jauh lebih memuakkan ketimbang buya.
Ini juga saya perhatikan betul-betul di televisi. Di mana kalau buya memakan mangsanya yang masih segar-segar. Sebuah bangkai peulandok yang dimangsa akan ditinggalkan bila sudah diganggu oleh berbangsa pemangsa yang lain seperti klueng putih atau rimueng pluek. Kita tahu, dominasi antara yang kuat kepada si lemah sangat rentan terjadi dalam rumusan kehidupan alam makhluk.
Sementara kalau meuruwa, ia bahkan akan menunggu sampai seluruh bekas bangkai itu tak lagi bersisa sedikit pun. Mungkin termasuk belatung-belatung yang sempat mengecap rasa atas tubuh yang telah busuk dan berbau menyengat, sampai menusuk hidung.
Akhirnya, saya juga dapati di sebuah gampong pinggiran, melalui seorang manusia tua yang berprofesi sebagai tukang pluek meuruwa. Tukang itu akan membuat perangkap dari nilon dengan ditaruh bangkai yang sudah berbau tepat di tengah perangkap.
Tukang pluek meuruwa akan mengoleksi bangkai ayam bila suatu saat musim ta’eun di gampong tiba. Ayam-ayam mati akan disimpan di suatu tempat agar selalu ada umpan untuk mendapatkan meuruwa.
Nah, tukang pluek meuruwa yang bertipe suka dengan bau, akan menyimpan bangkai berbau itu di sembarang tempat. Tipe seperti ini tentu tidak akan pernah disenangi oleh orang gampong. Bila disenangi dalam artian, belum tentu akan bebas bergaul dengan semua masyarakat. Tapi bila menyimpan di tempat yang jauh dari masyarakat, orang-orang tidak akan begitu peduli.
Namun demikian, di banyak gampong tetap saja, tukang pluek meuruwa sering terbatas pergaulannya. Itu karena, biasanya pakaian tukang pluek meuruwa umumnya berbau busuk. Mungkin karena sudah kebal bau, pemilik pakaian bagai tak merasa aroma apa-apa lagi.
Berbau itulah yang menjadi kegemaran meuruwa. Semakin berbau, biasanya semakin disukai dan meuruwa akan melahapnya sampai habis.
Di krueng gampong kami, ada sebuah likuk yang bernama lhok siren. Di sana, biasanya seluruh sampah-serapah berkumpul. Termasuk segala bangkai yang dihanyutkan oleh orang-orang gampong ke sungai.
Di sinilah, terlihat meuruwa yang sangat suka berguling-guling menghabiskan bangkai yang sudah sangat berbau. Sedang buya, mungkin tak sanggup lagi mendekatinya.
(Walaupun bengis dan agresif, ungkapan berunsur kata buya tetap saja ada yang disukai. Paling tidak dengan banyak celoteh tentang mata buaya, air mata buaya, dan sebagainya).
Lahirlah anggapan, rupanya (diam-diam), meuruwa jauh lebih berbahaya ketimbang buya. Dalam hal makan-memakan.
Mudah-mudahan Anda juga akan sempat melihat perilaku mereka. Ya, mungkin melalui berbagai tayangan televisi.[]
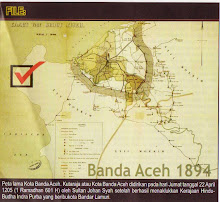

0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda