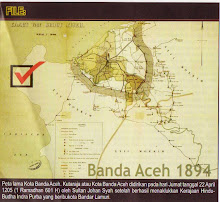berebut kursi
MENUNGGU ENDING DARI BEREBUT KURSI
(Sulaiman Tripa)
(Serambi Indonesia, 2 April 2009)
Belum ada satu rumah sakit pun di Aceh yang sudah menyediakan ruang atau kamar khusus bagi mereka yang akan gagal menjadi calon legislatif (caleg). Padahal, sebagaimana dituliskan Mukhtaruddin Yacob (Serambi, 28/03/09), potensi gangguan jiwa juga menghantui bagi para caleg di Aceh, di mana dengan jumlah 9.843 yang memperebutkan 736 kursi (DPR RI, DPR Aceh, DPR Kabupaten/Kota), berarti ada 9.107 yang akan tergeser. Ampuh Devayan (29/03/09), dengan bahasa lain memperingatkan pentingnya mempersiapkan diri dari sekarang.
Ada kemungkinan bahwa karena di Aceh juga memiliki rumah sakit jiwa, maka penyediaan kamar khusus tidak dibutuhkan lagi. Bisa jadi hal ini untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap orang-orang yang akan mengisi rumah sakit jiwa nantinya.
Masalah ini berbeda dengan di daerah lain. Kabarnya beberapa rumah sakit di Indonesia sudah mempersiapkan ruang atau kamar yang sangat ekslusif untuk pasien yang mengalami masalah gangguan jiwa. Kamar atau ruang tersebut memang bukan untuk rakyat biasa, tetapi untuk caleg yang tidak terpilih menjadi anggota legislatif. Ada caleg yang diprediksikan akan menjadi penghuni ruang atau kamar jiwa tersebut.
Ada hal yang menarik yang ingin disampaikan dalam tulisan ini. Pertama, bahwa keputusan untuk menghadirkan ruang tersebut, bagi pihak rumah sakit tentu sudah melalui pertimbangan yang matang. Sebuah kebijakan (tepatnya kebijaksanaan) dari pengelolan rumah sakit, tidak mungkin berdasarkan kalkulasi kosong, karena kebijaksanaan demikian menyangkut investasi modal.
Kedua, kebijaksanaan ini dilahirkan oleh pengalaman para ahli jiwa dalam hal mengikuti perkembangan masyarakatnya. Artinya, banyaknya orang yang akan mengalami depresi atau masalah kejiwaan pasca pelaksanaan pemilihan umum 9 April 2009 mendatang, bukanlah perhitungan tanpa dasar. Para ahli jiwa –dengan ilmu dan pengetahuannya—tentu sudah menganalisis hingga lahir kebijaksanaan seperti itu.
Di luar masalah yang dituliskan Mukhtaruddin Yacob dan Ampuh Devayan, sebenarnya ada persoalan yang penting diajukan: bahwa siapa saja sebenarnya yang termasuk dalam 9.843 orang yang berebut kursi legislatif itu? Pertanyaan ini sangat berkaitan bahwa dianggap sebagai apa kekuasaan legislatif?
Hal ini lebih lanjut berkaitan dengan konsep Trias Politica (kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif), dimaka fungsi legislatif adalah melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan terhadap pemerintahan, serta melakukan fungsi anggaran.
Nah pertanyaannya, bila 9.843 orang yang berebut kursi legislatif itu tidak dikaitkan dengan keinginan memperkuat kekuasaan legislatif, apa jadinya kekuasaan ini di masa mendatang.
Dalam kacamata hukum, bahwa proses legislasi yang harus dilakukan oleh legislatif nantinya merupakan dambaan banyak orang untuk kesejahteraan dan kebahagiaan. Proses legislasi pada akhirnya harus bisa menjawab proses menuju kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.
Pertarungan inilah yang sedang terjadi. Kegelisahan banyak orang kini mulai memuncak menunggu siapa saja yang akan mengisi kursi-kursi yang tersedia di legislatif tersebut –yang disebut dengan lembaga terhormat. Sedangkan pada saat yang sama, kita juga dengan segenap keprihatinan sedang menanti siapa saja yang akan mengisi rumah sakit yang sudah menyediakan ruang kejiwaan tersebut.
Kegelisahan patut saya ungkapkan dan terus-terang kegelisahan ini sudah berulangkali disampaikan media massa. Karena hal ini sudah diketahui oleh orang banyak, maka mungkin saja kegelisahan ini sebagai kegelisahan berjamaah.
Dugaan dan kegelisahaan yang sering diungkapkan banyak orang tersebut, sebenarnya lebih didasari oleh alasan-alasan sederhana yang sudah luput dari pantauan umum. Saya ingin menekankan frasa ”alasan-alasan sederhana” karena memang hal tersebut sudah dianggap sebagai sesuatu yang lazim. Orang-orang sudah menganggap hal ini sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar terjadi.
Pertama, legislatif dipandang sebagai tempat mencari rezeki. Di mana-mana, kursi legislatif itu didominasi oleh caleg yang sedang mencoba mencari peruntungan. Dalam posisi legislatif yang seperti ini, pada prinsipnya sama seperti orang yang ingin masuk pegawai negeri sipil. Ketika ada pengumuman, lalu orang berbondong-bondong mendaftar. Hal ini kemudian terbukti dengan banyaknya orang yang mengundurkan sebagai caleg karena sudah terdapat namanya dalam pengumuman calon pegawai negeri sipil.
Dengan alasan bahwa kursi legislatif sebagai peluang mendapat rezeki, maka untuk mendapatkan rezeki tersebut tidak apa-apa kalau dengan mengeluarkan modal terlebih dahulu. Konon, menurut rumah sakit yang sudah menyediakan kamar jiwa, bahwa karena alasan modal inilah yang menyebabkan banyak orang-orang yang tidak terpilih nantinya akan bermasalah dengan kejiwaannya.
Kedua, adalah sesuatu yang disindir Halim Mubary dengan satu kata yang bernama ”jampok” (Serambi, 21/03/09). Kata ini sangat dekat dengan fenomena ”tidak malu”. Kaitannya adalah tentang orang Aceh yang diklaim sebagai daerah agamis, tentu di dalamnya sepenuhnya orang-orang agamis. Masalahnya, salah satu indikator agamis itu adalah ”punya malu”. Dalam mengisi kursi untuk jabatan tertentu (termasuk legislatif), maka orang yang ”punya malu” tidak akan meminta jabatan atau meminta dirinya dipilih untuk jabatan itu.
Lalu adakah orang-orang yang seperti itu dalam penjaringan caleg di daerah kita? Kita bisa melihat wajah-wajah manis dengan senyum sumringah, selalu dihiasi dengan kata-kata ”pilihlah saya”, karena dengan memilih saya, maka ”akan begini atau akan begitu.” Menyedihkan ketika janji yang ditawarkan kadangkala hanya mengulang-ngulang sebagaimana juga dilakukan oleh caleg-caleg pada periode yang lalu. Sudah jutaan orang mengucapkan janji demi janji. Saya ingat sebuah televisi menanyakan seorang masyarakat, ”bagaimana nantinya seseorang waktu menjadi anggota dewan”, orang itu dengan lugu menjawab bahwa keadaannya sama saja. Lalu ada pertanyaan, apa yang dilakukan orang yang memahami seperti itu. Jawabannya sederhana, ”ambil yang dikasih, tapi di bilik suara, kita tentu punya pilihan sendiri.”
Ketiga, wajar bila ada yang mengungkapkan kegelisahannya terhadap profil lembaga legislatif di masa mendatang. Atas dasar apa seseorang dipilih? Apakah karena uang? Karena teman, keluarga, dan sebagainya? Hal ini semua sangat berpengaruh pada profil lembaga ini di masa mendatang.
Sejauhmana kualitas legislatif, pada akhirnya akan berakibat langsung kepada masyarakat. Proses regulasi, pengawasan dan anggaran yang akan menjadi tugas legislatif, sangat dipengaruhi oleh kualitas orang yang merumuskan regulasi, melakukan pengawasan, dan melaksanakan fungsi anggaran tersebut. Regulasi yang memihak rakyat, pengawasan yang berbasis untuk mensejahterakan rakyat, atau merumuskan anggaran yang juga berpihak, tentu sangat ditentukan oleh kualitas.
Apapun masalah dan kenyataannya, kita sebenarnya sedang menunggu ending dari orang-orang yang sedang berebut kursi. Jangan-jangan, orang-orang yang berkualitas, tetapi tidak terpilih pada pemilihan umum 9 April mendatang, juga akan merasakan ruang yang disediakan oleh rumah sakit jiwa. Entahlah. Kita doakan tidak seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberi keselamatan kepada kita semua dari dunia hingga akhirat, dalam kondisi terpilih atau tidak terpilih, kita semua tetap sehat lahir-batin.[]