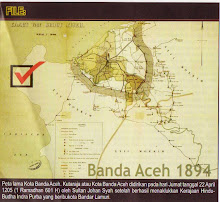BANJIR
ADA bayang-bayang baru di sebuah gampong. Bayang-bayang itu bernama banjir. Air yang mengalir di sungai, bisa seperti air laut yang memantik gelombang raya, berbias untuk melahirkan berbagai tafsir. Yang lebih dominan adalah ujung, bukan pangkal. Sama seperti pepohonan yang dibawa oleh air yang deras, berupa potongan sisa.
Gampong saya, beberapa waktu yang lalu juga menimpa banjir. Ada kebiasaan bagi anak muda tanggung di sana, ketika banjir datang sore hari, mereka akan memakai pakaian kotor dan menunggu di pinggir sungai sambil menunggu ada sisa pepohonan yang lewat.
Begitu terlihat, ada beberapa yang langsung bersiap. Siapa yang memegang lebih dulu, ia yang dianggap berkuasa. Sedang di pinggir, orang bersorak-sorai begitu ada yang menang dan ada yang kalah. Ini menjadi kebiasaan saat banjir datang sejak sore hari. Gulungan air coklat susu tidak dianggap menakutkan.
Namun apa yang terjadi dengan banjir yang terakhir? Datangnya pukul 23.00 malam. Jelas, tak memungkinkan anak muda tanggung untuk menunggu sisa pepohonan di pinggir sungai. Kejadian yang terakhir, membuat mereka harus menyelamatkan apa saja isi rumah karena air masuk ke gampong sampai mencapai ketinggian 1,5 meter.
Tua-muda, remaja-bayi, akhirnya memilih mengungsi di pinggir bukit. Kali ini, mereka sudah mulai sering bertanya, kenapa banjir? Ketika banjir menjadi kebiasaan dan kualitas biasa-biasa saja, sudah terlanjur dianggap bukan sebagai keanehan. Apalagi anak-anak memang sesekali suka bermandi ria di depan rumah.
Padahal, banjir, mau besar atau kecil, sebenarnya adalah masalah. Banjir teuka karena alam sedang tak normal. Tapi orang yang mengingatkan bahwa manusia sering membuat ketidaknormalan alam, sering dianggap sebagai angin lalu.
Lihatlah yang terakhir, di mana-mana, ada banjir. Rumah-rumah di gampong, yang umumnya terletak tak jauh dari sungai, sudah pasti turut dikunjungi genangan air dan sisanya adalah, tentunya lumpur. Tempat tinggal di Banda Aceh, juga seperti itu. Pada saat yang sama, dengan beberapa banjir.
Di televisi, di radio, di suratkabar, berita banjir terdengar di mana-mana. Di Jakarta lumpuh, karena banjir. Di Bogor, Bandung, Tanggerang, semua banjir. Apalagi di sebagian wilayah Jakarta yang tiap tahun dikunjungi banjir.
Ketika sesuatu sudah sangat akrab dengan kehidupan kita, seperti banjir, misalnya, maka itu sudah tidak dianggap lagi sebagai sebuah keanehan. Sesuatu yang sudah sering, sudah lazim, tidak lagi terlihat aneh. Sama sekali tidak.
Anda yang tinggal di kawasan yang langganan banjir, tidak pernah merasa ganjil lagi dengan banjir. Seperti beberapa kawasan di Jakarta, ketika musim hujan tiba, maka mereka pun bersiap-siap untuk menghadapi yang namanya banjir.
Tak ada keanehan, menyebabkan kesigapan oleh pihak yang berwenang, juga akan berlangsung biasa-biasa saja. Bayangkan bila sebuah kawasan karena terlalu sering banjir, tapi upaya untuk menghindari banjir tidak dilakukan secara serius. Yang banyak adalah menyediakan bantuan ketika banjir tiba. Ada orang yang kehilangan makanan karena banjir, lalu diberikan bantuan sosial berupa makanan untuk korban banjir. Sedang banjir terus ada tiap tahun.
Banjir, telah menyebabkan rapuhnya konsep matematika. Persoalan kemanusiaan menjadi ruang untuk program baru. Sangat ironis bila efektivitas program yang semestinya, menjadi berkurang.
Kita memang aneh. Semoga tidak menjadi selalu aneh![]
(Sulaiman Tripa)