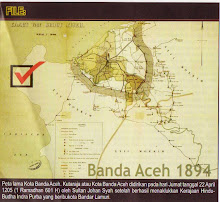Khanduri dan Keurija
ADA dua hal di sekitar kita yang bermakna (hampir) sama, yaitu khanduri dan keurija. Rasanya, semua kita tahu apa itu khanduri, walau belum tentu mengerti apa itu keurija. Dua hal itu, kurang lebih sama. Khanduri atau kenduri, sederhananya adalah makan bersama. Jadi apapun yang dimakan secara bersama-sama, itu bisa dinamakan dengan kenduri. Tapi khanduri akan lebih dalam dari sekedar makan-makan (pajoh seumajoh). Setiap khanduri pasti ada doa bersama.
Seorang teman, dengan menyentil, bertanya begini: kok di Aceh itu selalu diakhiri dengan makan-makan? Rupanya, ia menyaksikan seorang gampong yang habis berkelahi sampai berdarah, lalu menjalani proses perdamaian dan diakhiri dengan makan bersama disertai berdoa.
Asumsi saya, pada berdoa itulah titik penting dari khanduri sehingga seseorang yang sudah saling berdarah-darah tapi kemudian bisa menjadi saudara. Dalam konteks resolusi konflik, seseorang yang mungkin sudah berdarah hatinya tapi bisa saling memaafkan, merupakan kenyataan kekayaan imaniah yang luar biasa. Terus-terang, biasanya sangat berat untuk bisa seperti itu, tapi di gampong-gampong di Aceh, penyelesaian secara damai ternyata berlangsung mudah. Menurut saya didoa itu yang penting dalam setiap pelaksanaan khanduri. Lalu bagaimana hubungannya dengan keurija?
Dalam masyarakat Aceh dikenal ada yang namanya keurija udep dan keurija mate. Walau sama-sama disebut keurija, tapi perlakuan terhadap keduanya sangat berbeda. Termasuk dalam hal penyambutan tamu. Dalam keurija mate, tidak ada unsur kemeriahan, seperti sebuah keharusan dalam keurija udep. Keurija mate lebih sering mendekatkan kita kepada akhirat ketimbang dunia.
Biasanya, seberada apapun pelaksana keurija mate, semewah apapun akan pelaksanaan penyambutan tamu, tapi tetap tak tepat bila disebut meriah. Kemeriahan inilah yang akan menjadi penanda seseorang yang membuat keurija udep agar terbentuk semegah-megahnya.
Dalam salah satu proses keurija, akhirnya berhubungan sangat erat khanduri. Tak tertutup kemungkinan, secara dominan orang akan menganggap sama. Tapi menurut saya, keurija itu mesti berlangsungnya khanduri dan khanduri dapat saja berlangsung tanpa keurija.
Nah, khanduri menjadi penanda adanya rasa syukur dari sebuah keurija. Dalam konteks yang lain, khanduri dalam keurija mate, selalu berhubungan dengan keinginan tuan rumah (walau sedang berduka) untuk memuliakan tamu sehormat-hormatnya. Bukankah khanduri dapat saja berbentuk segelas air putih?
Masalahnya, selain untuk memuliakan, juga ada untuk gagah-gagahan. Ada juga orang yang memanfaatkan keurija mate sebagai sebuah kepentingan yang harus diperjuangkan. Itu persoalan lain. Tapi ini sangat berpengaruh kepada tingkat meriah atau tidaknya sebuah keurija mate.
Sebenarnya sangat tidak etis menyambut keurija mate dengan meriah, karena kata itu hanya cocok untuk keurija udep. Tapi tahukah Anda bahwa disekitar kita ternyata hampir tidak ada orang yang bisa membedakan mana keurija mate atau keurija udep. Kita sering melihat ada keurija udep dalam keurija mate. Orang-orang didalam rumah duka, menganggap orang yang berkunjung (tamu) sebagai raja yang harus dilayani. Sedangkan sipengunjung menganggap itu sebagai bentuk lain penghormatan yang punya hajat. Sehingga tidak jarang tamu tidak hanya makan isi hidangan dirumah duka, tapi piring-piring tempat hidangan pun dibawa pulang.
Penanda lain dari semaraknya keurija mate di gampong kita adalah banyak makanan dan banyak orang hebat yang datang. Masalahnya bukan pada orang hebat, tapi pada berbagai persoalan kemudian yang harus ditanggung oleh empunya rumah duka, dimana orang hebat yang datang harus difasilitasi oleh orang yang berduka. Sementara empunya rumah duka umumnya untuk menyediakan secangkir teh saja sedikit susah.
Orang-orang datang dengan berbagai rupa. Mereka ingin berkunjung ke rumah duka dengan tujuan untuk memberikan semangat kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Awalnya, kunjungan itu sangat membantu. Tapi akhir-akhir ini, sebagian tamu tidak lagi datang untuk memberi semangat, tapi untuk mengambil semangat. Hanya sedikit tamu yang tinggal yang benar-benar memberi semangat kepada seluruh keluarga korban yang ditinggalkan.
Hakikat keurija mate sudah tidak ada lagi. Orang-orang yang datang ke keurija mate, sepertinya sudah menganggap bahwa itu bukan lagi sebagai keurija mate, tapi sudah merupakan keurija udep. Keurija udep, tentu sangat didominasi oleh hiburan-hiburan yang tidak sakral, walau itu tidak berarti selalu duniawi saja. Orang-orang yang sedang mengunjungi keurija udep, mungkin sangat jarang mengingat kematian yang datang kapan saja. Inilah yang sedang dibangun di gampong kita. Kita bisa menyaksikan sendiri, ada orang-orang yang bersenang-senang dalam keurija mate, sehingga pelaksanaan keurija mate, hampir tidak ada beda dengan keurija udep.
Sebagian gampong sudah terjebak dalam hedonisme kehidupan itu, sehingga terkesan si empu rumah keurija mate seolah menjadi pemberi kesenangan kepada para tamu yang melayat.
Dengan kondisi seperti ini masihkah gampong kita bisa disebut sebagai gampong yang beragama? Karena di dalam gampong, kita banyak menyaksikan hal-hal yang tidak pernah diperkirakan dulunya kini sudah berlangsung, dan ironisnya bagia sebagian orang ini menjadi hal yang lazim ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kita hampir tidak bisa lagi membedakan mana yang keurija mate dan mana yang keurija udep. Bukankah dari keurija mate dan keurija udep itu, kita bisa melihat konteks khanduri secara utuh? [Sulaiman Tripa]