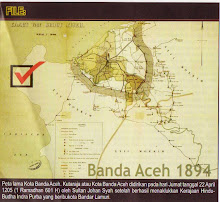"Starblack" dan Kopi Aceh
Tradisi minum kopi dikenal di banyak masyarakat di berbagai negara. Tetapi, barangkali hanya ditemukan di Aceh, entah di kota maupun desa, sejak subuh hingga tengah malam warga silih berganti ke kedai kopi.
Di desa, sejak dulu orang biasa ke kedai kopi setelah shalat subuh," kata Sulaiman Tripa, peneliti budaya dan penulis beberapa buku di Banda Aceh. Sulaiman sendiri pernah bekerja di kedai kopi kakaknya di Trieng Gading, Pidie, saat masih duduk di bangku SLTP.
Masalah kemudian muncul. Beberapa waktu lalu Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf, yang juga "pengunjung" kedai kopi, sempat gusar karena banyak pegawai negeri tidak di tempat ketika jam kerja. Ia melakukan "sweeping" ke kedai kopi favorit pejabat di Banda Aceh. Sejak itu orang berseragam pegawai negeri gerah duduk di kedai kopi.
Kedai kopi juga mengundang masalah rumah tangga. "Sarapan yang disediakan istri kerap tidak disentuh. Banyak suami memilih sarapan di kedai kopi," kata Tarmizi, pengusaha kedai kopi di dekat Bandara Blang Bintang, Aceh Besar.
Berubah fungsi
Menurut Sulaiman, fungsi kedai kopi telah berubah dari tempat minum kopi menjadi sejenis ruang sosial, tempat tukar-menukar informasi.
Pendapat senada dikemukakan Teuku Kemal Fasya, antropolog di Universitas Malikussaleh, Lhok Seumawe. Di kedai kopi tersedia jawaban atas hal-hal yang tidak terselesaikan melalui jalur formal.
Di kedai kopi, warga berbincang mengenai masalah keluarga, politik lokal, nasional, dan isu yang sedang hangat dalam sorotan pers. Pergantian pejabat kerap lebih dulu terdengar di kedai kopi, termasuk skandal pejabat.
Sosok kedai kopi itu sendiri mungkin akan mengejutkan mereka yang belum pernah ke Aceh. Di Banda Aceh, ratusan manusia berjubel di beberapa kedai kopi favorit. Kendaraan roda dua dan empat diparkir memanjang seperti di kompleks pertokoan.
Kedai kopi umumnya berada di sebuah atau beberapa ruko. Ada pula yang berbentuk warung seperti di Jawa. Dapat dibayangkan ketika ruangan sempit tersebut dijejali manusia pada tengah hari yang terik. Ditambah lagi asap rokok. Tetapi, semakin berjubel manusia justru semakin menarik minat pelanggan.
"Di kedai kopi orang dapat bertemu segala rupa dan jabatan manusia. Gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, pengusaha, kontraktor, guru, ulama, bahkan pengangguran," ujar Kemal Fasya. Lebih mudah menemui pejabat atau pengusaha di kedai kopi ketimbang di kantornya. "Pertemuan di kedai kopi membuka jalan bagi langkah selanjutnya."
Suasana ini sulit ditemukan di daerah lain. Di Jawa, misalnya, jangankan gubernur atau bupati, seorang pejabat eselon II atau III di daerah pastilah enggan duduk di kedai kopi bersama warga biasa atau penganggur karena dianggap dapat mencederai wibawa korps pegawai negeri.
Pelepas stres
Lebih seru komentar yang terbetik di dunia maya seputar keberadaan kedai-kedai kopi khas Aceh ini.
Seorang blogger, Dudi Gurnadi dan teman-teman misalnya. Ia memelesetkan "warkop" di Aceh ini dengan sebutan "Starblack".
Kata Starblack merupakan kata plesetan dari warung kopi internasional yang saat ini merambah di berbagai belahan dunia, Starbucks. Warna hitam kopi di kedai-kedai Aceh, serta cita rasa yang tersendiri, membuat kopi Aceh cocok disebut oleh blogger ini sebagai Starblack.
Blogger lain menyatakan, kedai kopi di Aceh juga menjadi semacam tempat dugem (dunia gemerlap). Tiadanya tempat hiburan di Aceh seperti di ibu kota, diskotek, bioskop, ataupun kelab malam yang menyuguhkan musik hidup lengkap dengan hiburan-hiburannya, membuat kedai kopi Aceh sebagai salah satu "tempat hiburan" yang menyenangkan bagi orang-orang Aceh.
Nia (29), misalnya. Pekerja kemanusiaan di salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berafiliasi dengan pemerintahan Amerika Serikat ini mengaku ingin pergi ke Nanggroe Aceh Darussalam karena kangen kongko-kongko dengan teman-teman koleganya di kedai kopi Aceh. Entah di kedai Ayah-Solong, Ulee Kareng, atau di Warkop Chek Yukee, di Jalan Pinggir Kali, Banda Aceh.
Lain lagi dengan kalangan kampus ini. "Ketika tiba di kedai kopi, hal pertama yang kami lakukan membaca koran lokal," ujar seorang mantan aktivis mahasiswa. Setelah itu, dimulai pembahasan isu menarik dalam koran tersebut. Masing-masing punya pendapat dan kerap tidak masuk akal. "Maka, kami menyebut ke kedai kopi itu meng-update fitnah," ujarnya.
"Masalah apa saja dapat diselesaikan di kedai kopi," ujar Tarmiji (42), pengusaha kedai kopi Pak Geuchik, di dekat Bandara Blang Bintang, Aceh Besar. Ia merujuk Jamil, kontraktor gurem, yang ikut berbincang saat itu. Ketika membutuhkan tenaga tukang bangunan, Jamil cukup menyebarkan informasi di kedai kopi. Esoknya beberapa tukang menemui Jamil di kedai yang sama.
Ketika darurat militer masih diberlakukan, bencana mulai menimpa mereka yang masih nekat ke kedai kopi. Apalagi kedai kopi merupakan salah satu target sweeping aparat keamanan.
Mereka yang dicurigai identitasnya diangkut ke markas militer atau Polri. Di Teupian Raya, beberapa tahun lalu, aparat keamanan membakar kedai kopi setelah sebuah bom meledak dekat jembatan dan menewaskan tiga anggota pasukan Siliwangi. Kedai yang merupakan satu-satunya bangunan dekat lokasi kejadian dicurigai sebagai pos pengendalian serangan bom itu.
Teungku Yahya, penasihat Teungku Abdullah Syafei, panglima perang Gerakan Aceh Merdeka (GAM), harus menukar keinginan duduk di kedai kopi di Pidie dengan nyawanya. Aparat keamanan ternyata sudah mengetahui rute favorit gerilyawan GAM. Teungku Yahya pun tewas kena peluru aparat.
Perubahan
Suasana kedai adalah salah satu kunci sukses bisnis kedai kopi di Aceh. Kedai kopi milik H Nawawi di Ulee Kareng, Solong Banda Aceh, misalnya. Kedainya selalu ramai, bahkan sering pengunjung berdesak-desakan duduk di kedainya.
Keributan? Tidak juga pernah terjadi keributan maupun keluhan. Padahal, setiap hari rata-rata 2.500 orang minum kopi di kedai Nawawi yang dilayani 13 karyawan itu.
Di Ulee Kareng, harga secangkir kopi biasa Rp 3.500 dan kopi susu Rp 6.000. Berarti, setiap hari ada perputaran uang sekitar Rp 10 juta.
Hebatnya lagi, harga di kedai-kedai kopi ini juga bisa menjadi semacam "indikator ekonomi" di Aceh.
"Sebelum tsunami (2004), penghasilan Rp 20.000 per hari dapat memenuhi kebutuhan hidup. Harga secangkir kopi hanya Rp 1.000. Sekarang penghasilan Rp 50.000 tidak cukup. Harga secangkir kopi sudah Rp 2.500," ujar Ramond. Ramond (64) adalah seorang pengemudi becak bermotor yang kerap mangkal di depan Hotel Sultan, Banda Aceh.
Di sana, harga secangkir kopi lebih dipercaya sebagai indikator baik-buruknya keadaan ekonomi. Kenaikan harga BBM atau kebijakan makro lain adalah hal berikut. Di sini, ke kedai kopi adalah bagian dari irama kehidupan dan dianggap menyangkut "hak asasi manusia".
Sumber: Maruli Tobing & Mahdi Muhammad (Kompas, Minggu, 02 Desember 2007)