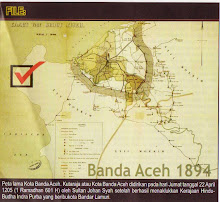KASUS
DALAM bidang kesehatan, gampong kita seperti sedang banyak kasus. Berbagai masalah yang menimpa orang-orang, dari hari ke hari makin banyak. Belum selesai satu kasus, timbul kasus lainnya.
Kasus flu burung (avian influenza) dan kasus formalin, adalah dua kasus berbeda. Akhir-akhir ini, kasus itu kembali menggusar kita. Padahal, porak-poranda karena tsunami saja belum semua orang bisa berbenah, walau sudah lebih dua tahun. Kasus terbaru di Aceh itu seolah memberi tanda bahwa masih perlu banyak usaha untuk memberi makna hidup bagi sesama.
Saat seperti inilah, sepertinya kemampuan kita sedang diuji. Dalam berbagai bencana, kita padahal selalu mendapat tanda bahwa banyak hal yang harus diperbaiki. Namun pada kenyataannya, kekhilafan (entah benar itu khilaf) selalu terjadi. Selalu berulang.
Selalu saja, saat ada bencana, kita baru bergerak. Itu pun masih terhambat di sana-sini. Saat ancaman kematian membuncah, kita juga masih disibuki terlebih dahulu dengan pembentukan panitia, teken kanan-kiri, rumuskan anggaran, baru bergerak. Padahal, kasus serupa yang terjadi di seluruh Indonesia dengan pemberitaan yang luar biasa, seharusnya sudah membuat kita bersiap-siap.
Sudah seharusnya pemerintah, ketika terjadi kasus di daerah lain, harus sudah menyiapkan berbagai hal untuk antisipasi. Para intelektual, seharusnya sudah memiliki semacam hasil survei, atau malah hasil penelitian secara mendalam dan konkret tentang berbagai kemungkinan mewabahnya penyakit.
Demikian juga mereka yang bergerak di bidang kesehatan (entah itu pemerintah atau nonpemerintah), seharusnya sudah selesai melaksanakan penyuluhan untuk masyarakat dan kawasan yang berpotensi terjangkit.
Demikian juga media. Menurut saya, media juga harus lebih responsif untuk melakukan reportase langsung ke lapangan, lalu melakukan cek ulang ke pihak yang berwenang. Salah satu kekurangan media dalam kasus ini, adalah lebih menonjolkan laporan para pihak sebagai sumber utama ketimbang kajian lapangan yang dominan berada sebagai sumber kedua.
Komunikasi ini saya kira belum terbangun. Semua orang mengatakan tugasnya sudah dilakukan. Para orang yang bertanggung jawab, misalnya, lebih condong asal mengeluarkan komentar ketimbang menurunkan tim yang benar-benar memiliki kapasitas ke lapangan, melihat secara langsung, kaji secara mendalam.
Selama ini yang terjadi, jauh dari harapan seperti itu. Seolah-olah, semua hal lalu menjadi kepentingan politik masing-masing. Akhirnya lebih banyak berbicara daripada berbuat.
Untuk sekelas wabah flu burung yang nyatanya sangat membahayakan, fenomena seperti itu seharusnya dihindari. Bahasa kasarnya, janganlah bermain-main dengan sesuatu yang sangat membahayakan nyawa manusia.
Saya kira saat seperti ini pula diuji, dengan gerak secepat kilat agar bisa menghasilkan hasil penelitian yang up to date. Lalu mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Inilah pentingnya kapasitas seseorang pemegang jabatan tertentu, yang sering dikatakan pejabat yang berwenang. Kalau tidak mampu seperti itu, berarti ada yang salah dengan penempatan.
Dalam kasus formalin demikian juga. Jangan sampai seperti kata orang tua kita dulu, pula lada watee trok Belanda (tanam lada waktu sampai Belanda). Itu akan terlambat. Bayangkan, lada baru ditanam saat Belanda yang mau membeli sudah sampai ke tempat kita.
Tamsil itu sangat bermakna untuk kita dalam memberi makna bagi hidup sesama. Apalagi di Aceh banyak orang yang masih sedang menuntaskan banyak beban hidupnya.
Kasus formalin menjadi ibrah bagi kasus lain yang mungkin saja hadir. Badan berwenang sudah seharusnya untuk meneliti segala sesuatu sebelum orang lain menemukannya. Para intelektual juga harus selalu mencium kelainan-kelainan dalam masyarakat. Inilah hakikatnya pengabdian.
Di Aceh sekarang cukup banyak elemen untuk mendeteksi segala keganjilan. Banyak lembaga yang memiliki peralatan canggih di sini. Seharusnya itu bisa dioptimalkan peran agar masyarakat terbebas dari segala gelisah.
Di sebagian kawasan, sudah muncul kasus lain, orang meninggal tiba-tiba. Ini membuat gelisah berlipat-lipat.[sulaiman tripa]